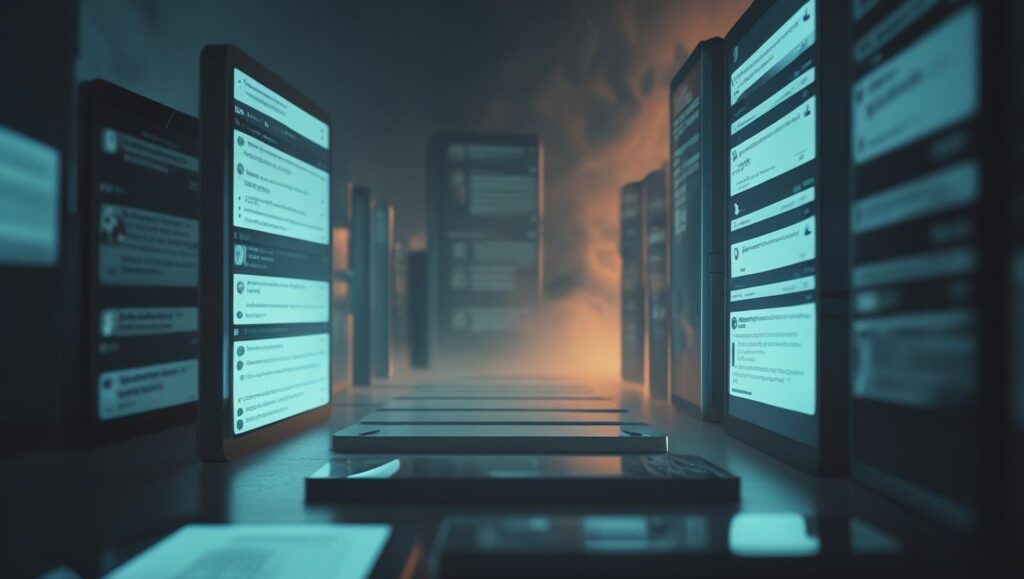Informasi memainkan peran penting dalam kehidupan politik, khususnya dalam membentuk persepsi pemilih. Dalam konteks demokrasi modern, pemahaman tentang sumber informasi yang diandalkan masyarakat serta tingkat kepercayaan terhadap saluran-saluran tersebut menjadi fondasi untuk menilai kesehatan proses politik.
Tulisan singkat ini memuat temuan dari penelitian “Disinformation and Election Propaganda: Impact on Voter Perceptions and Behaviours in Indonesia’s 2024 Presidential Election” oleh Maria Monica Wihardja, Burhanuddin Muhtadi, dan Lee Sue-Ann (2025), yang salah satu laporannya memaparkan sumber informasi politik utama dan media yang paling dipercaya oleh pemilih Indonesia.
Studi tersebut menggunakan sampel nasional berbasis panel dua gelombang dengan 2.020 responden pada Gelombang 1 (November 2023) dan 1.919 responden yang sama pada Gelombang 2 (Februari 2024). Responden tersebar di 34 provinsi, mewakili populasi pemilih berusia minimal 17 tahun (atau sudah menikah jika di bawah 17 tahun), dengan komposisi demografis (gender, wilayah urban-rural, kelompok usia, agama, etnis, dan provinsi) yang merefleksikan populasi nasional.
Secara umum, televisi (TV) tradisional merupakan sumber informasi politik terpenting bagi masyarakat Indonesia, dengan 39,5% responden mengaksesnya setiap hari atau hampir setiap hari untuk berita terkait pemilu.
Peringkat kedua ditempati oleh aplikasi pesan WhatsApp (30,8%), diikuti percakapan langsung dengan keluarga, teman, atau rekan kerja (26,6%). Platform digital seperti YouTube (24,1%), TikTok (21,2%), Facebook (18,0%), dan Instagram (13,7%) juga signifikan, mengungguli portal berita online (11,0%). Sementara itu, media cetak (koran/majalah) menempati posisi terendah (0,5%).
Twitter (kini X) menunjukkan tingkat relevansi yang sangat rendah, dengan hanya 3,2% responden menggunakannya secara harian untuk berita pemilu, angka terendah lainnya adalah SMS (1,4%) dan radio (3,2%).
Rendahnya penggunaan Twitter ini konsisten di semua kelompok usia dan preferensi politik, mengindikasikan ketidakefektifannya sebagai saluran komunikasi politik utama dibandingkan platform visual seperti TikTok atau aplikasi pesan seperti WhatsApp.
Pola ini mengalami perubahan pada generasi muda (usia 15–24 tahun). Kelompok ini menyebut TikTok sebagai sumber berita pemilu paling dominan (34,0% mengaksesnya setiap hari/hampir setiap hari), diikuti WhatsApp (28,9%), TV (28,2%), Instagram (25,3%), dan YouTube (22,6%).
Temuan ini mengonfirmasi pergeseran generasional dalam pola konsumsi berita dan peran sentral internet bagi kaum muda, yang mencakup 20% dari 204,8 juta pemilih Indonesia.
Meskipun demikian, penggunaan media sosial tidak seragam di antara pendukung kandidat. Pendukung Ganjar-Mahfud, misalnya, secara signifikan lebih jarang mengakses TikTok, YouTube, dan Instagram dibandingkan pendukung Anies-Muhaimin (78%) atau Prabowo-Gibran (73%). Hal ini berkorelasi dengan penetrasi internet yang lebih rendah (67%).
Meskipun media sosial dan aplikasi pesan banyak digunakan, tingkat kepercayaan publik terhadapnya sebagai sumber informasi tepercaya tergolong rendah. Secara keseluruhan, TV dinobatkan sebagai media paling dipercaya (41,9%) responden (“percaya” atau “sangat percaya”), diikuti percakapan langsung dengan keluarga/teman/rekan (39,1%), dan percakapan dalam konteks sosial (26,2%).
Media cetak (16.4%) menempati peringkat keempat setelah TV, percakapan langsung, dan percakapan sosial (26.2%), diikuti WhatsApp (14.6%) serta portal berita online (13.5%) dan YouTube (13.8%).
Portal berita online (13,5%) relatif lebih dipercaya daripada Facebook (9,2%), TikTok (9,2%), dan Instagram (8,1%). Twitter (4,4%), Messenger (4,4%), dan Telegram (1,8%) adalah yang paling tidak dipercaya. Pola serupa terlihat pada generasi muda: TV (40,7%) dan percakapan langsung (40,3%) tetap paling dipercaya, disusul media cetak (20,8%).
TikTok hanya dipercaya oleh 8,9% responden muda, menempati peringkat kesembilan. Rendahnya kepercayaan ini berkorelasi dengan persepsi maraknya berita palsu (hoaks), ujaran kebencian, dan fitnah di platform digital. Sebanyak 49,7% responden mengaku jarang hingga sering menemukan hoaks di media sosial/aplikasi pesan, jauh lebih tinggi daripada di media arus utama (26,8%) atau percakapan langsung (22,8%).
Temuan menarik terkait penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam kampanye terungkap melalui analisis dampak deepfake, konten sintetis yang dirancang meniru figur nyata. Penelitian ini mendokumentasikan dua contoh.
Pertama, video deepfake Prabowo Subianto berpidato dalam bahasa Arab (19% responden terpapar, 28% percaya keasliannya), dan, kedua, audio deepfake Surya Paloh (ketua NasDem) yang sedang “menegur” Anies Baswedan (23% terpapar, 18% percaya).
Meski kualitasnya digambarkan sebagai “rudimentary“, konten ini menjadi bukti pertama penggunaan deepfake secara masif dalam pemilu Indonesia. Lebih jauh, deepfake Suharto yang telah meninggal, menyuarakan dukungan untuk Partai Golkar, dipercayai oleh 14,5% responden.
Temuan ini menunjukkan kerentanan segmen pemilih terhadap disinformasi berbasis AI, meski mayoritas (60-75%) mampu mengidentifikasi ketidakasliannya.
Kesimpulannya, meskipun media digital, khususnya TikTok dan WhatsApp, telah menjadi saluran informasi politik utama, terutama bagi generasi muda, kepercayaan publik justru lebih tinggi pada sumber tradisional seperti televisi dan interaksi tatap muka secara sosial.
Media sosial, meskipun banyak diakses, belum mampu membangun kredibilitas setara. Pada pemuda, meskipun TikTok mendominasi akses informasi, tingkat kepercayaan tertinggi tetap diberikan kepada TV dan percakapan langsung.
Fenomena ini mencerminkan kesadaran akan risiko mis/disinformasi di dunia online sekaligus menunjukkan ketahanan (resilience) literasi media masyarakat Indonesia.
Temuan ini menegaskan kompleksitas lanskap informasi politik: dominasi akses tidak selalu sejalan dengan kredibilitas yang dirasakan, sementara teknologi baru seperti AI membawa tantangan sekaligus peluang dalam membangun, atau merusak, kepercayaan pemilih.
Penulis: Redaksi Insight by Research
Baca Juga:
Echo Chamber dalam Pemilu 2024 di Indonesia
Echo Chamber: Dinamika Pembentukan dan Konsekuensi Sosial di Ruang Digital