Islam mengalami masa keemasan antara abad ke-8 hingga ke-12, di mana dunia Muslim menjadi pusat kemajuan ilmu pengetahuan, ekonomi, dan budaya. Kota-kota seperti Baghdad, Cordoba, dan Kairo menjadi simbol kemajuan, menarik ilmuwan, filsuf, dan pedagang dari berbagai wilayah.
Tokoh-tokoh seperti Al-Khawarizmi (penemu aljabar), Ibnu Sina (perintis kedokteran modern), dan Al-Farabi (filsuf terkemuka) lahir dari dinamika intelektual zaman ini. Namun, pada episode selanjutnya, setelah abad ke-12, peradaban Islam mulai mengalami kemunduran.
Ahmet Kuru, seorang profesor ilmu politik dari Universitas San Diego, dalam bukunya “Islam, Authoritarianism, and Underdevelopment” (2019), menelusuri akar masalah ini melalui analisis historis dan menawarkan penjelasan bahwa aliansi ulama-negara adalah biang keladinya.
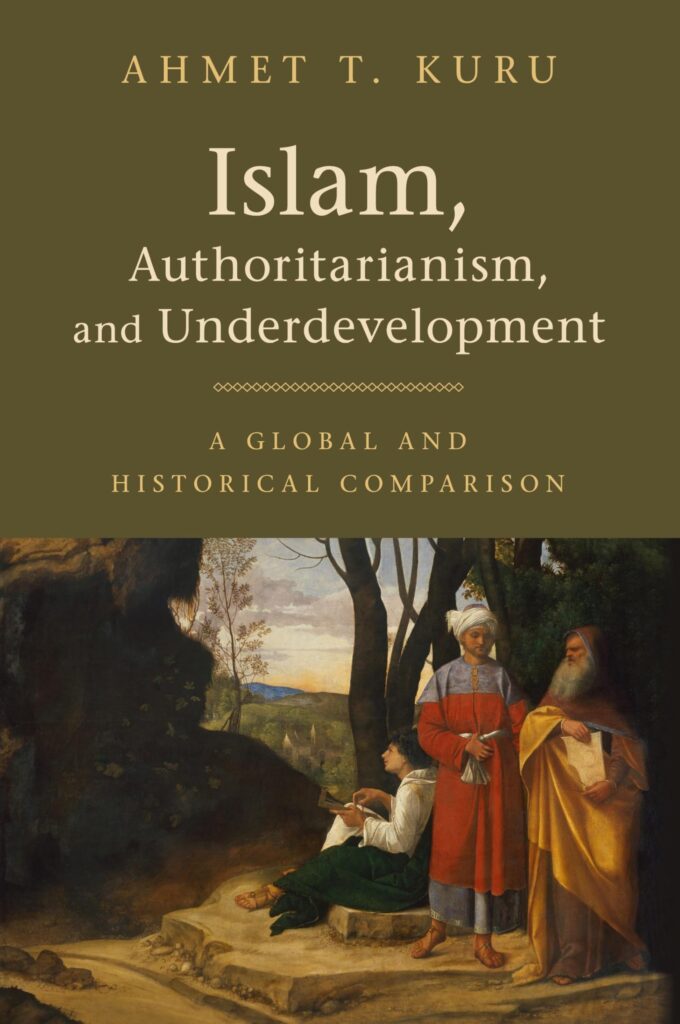
Tulisan ringkas ini memuat alur kronologis untuk memperjelas bagaimana argumen Kuru terbentuk. Bahan penulisannya merupakan ringkasan dari buku tulisan Kuru.
Masa Keemasan (Abad ke-8 hingga ke-11): Kemandirian Ulama dan Pedagang
Pada periode ini, kemajuan Islam ditopang oleh dua kelompok utama: ulama (cendekiawan agama) dan kelas pedagang. Pedagang, yang kaya dari perdagangan jalur sutra dan rempah, mendanai kegiatan intelektual, termasuk penerjemahan karya Yunani dan pengembangan sains. Ulama, di sisi lain, tidak sepenuhnya bergantung pada negara.
Mereka mendapatkan dukungan finansial dari pedagang dan tetap independen secara politik. Contohnya, Ibnu Sina dan Al-Farabi bisa berkarya tanpa intervensi penguasa karena sistem patronase ini.
Kemajuan ini didukung oleh struktur politik yang terdesentralisasi. Kekhalifahan Abbasiah (750–1258) memberikan otonomi kepada wilayah-wilayah, memungkinkan kota-kota seperti Baghdad dan Kairo menjadi pusat inovasi. Sistem ekonomi yang terbuka juga mendorong pertukaran ide dengan peradaban lain, termasuk India, Persia, dan Yunani.
Perubahan Struktural Abad ke-11: Awal Aliansi Ulama-Negara
Situasi berubah drastis pada abad ke-11. Kekhalifahan Abbasiah menghadapi ancaman internal dari kelompok Syiah dan eksternal dari invasi Turki. Untuk mengonsolidasi kekuasaan, penguasa Sunni Abbasiah membentuk aliansi dengan ulama ortodoks. Langkah ini diperkuat dengan penerapan sistem iqta, yakni pemberian hak pengelolaan tanah kepada militer sebagai imbalan layanan. Sistem ini mengalihkan kontrol ekonomi dari pedagang ke tangan negara dan elite militer.
Untuk memperkuat legitimasi, negara mendirikan madrasah Nizamiyyah (sekolah agama) yang melatih ulama yang loyal terhadap negara. Ulama yang sebelumnya independen mulai terkooptasi oleh negara. Mereka bertugas memberikan legitimasi teologis bagi kebijakan penguasa, seperti memerangi kelompok Syiah dan pemikir rasionalis (Mutazilah). Di sini, pemikiran Al-Ghazali (1058–1111) diadopsi secara selektif oleh negara.
Sebagai catatan: Perlu ditekankan bahwa Al-Ghazali sendiri bukanlah penyebab kemunduran, sebagaimana sering disalahpahami oleh pemikir Barat. Karyanya, seperti “Tahafut al-Falasifah” (Kerancuan Para Filsuf), memang mengkritik filsafat rasionalis, tetapi kritik ini awalnya adalah bagian dari debat intelektual yang sehat.
Namun, aliansi ulama-negara memanfaatkan argumen Al-Ghazali untuk menjustifikasi penindasan terhadap pemikiran alternatif. Pemikiran Al-Ghazali yang kompleks, yang juga mencakup dimensi tasawuf dan logika, direduksi menjadi doktrin kepatuhan mutlak pada otoritas agama, yang kemudian dijadikan alat politik untuk mempertahankan status quo.
Invasi Mongol dan Crusader (Abad ke-12–14): Konsolidasi Aliansi
Invasi Mongol (1258) yang dipimpin oleh Hulagu Khan menghancurkan Baghdad dan serangan Crusader (1096–1291) memperparah ketergantungan negara pada ulama. Penguasa Muslim seperti Kesultanan Mamluk membutuhkan legitimasi agama untuk memobilisasi perlawanan. Aliansi ulama-negara semakin kokoh: ulama mendukung kebijakan militer, sementara negara memberikan dana dan perlindungan kepada institusi keagamaan.
Pada fase ini, kelas pedagang dan intelektual independen semakin terpinggirkan. Madrasah Nizamiyyah hanya mengajarkan kurikulum ortodoks, sementara karya filsafat dan sains dianggap bidah. Contohnya, pemikiran Ibnu Rusyd (Averroes) yang rasionalis dilarang, dan buku-bukunya dibakar di Cordoba.
Era Kekaisaran Sunni (Abad ke-15–18): Stagnasi Intelektual
Tiga kekaisaran besar, yakni Ottoman (Sunni), Safavid (Syiah), dan Mughal, muncul pasca-invasi Mongol. Meski kuat secara militer, mereka melanjutkan model aliansi ulama-negara. Di Ottoman, misalnya, ulama diangkat sebagai hakim dan penasihat sultan, sementara perdagangan dikontrol ketat oleh negara. Kebijakan ini membunuh inovasi: tidak ada penemuan besar dalam sains atau teknologi selama periode ini, berbeda dengan Eropa yang sedang mengalami Renaisans.
Kuru mencatat, di Eropa, pemisahan gereja-negara dan kebangkitan universitas otonom (seperti Bologna dan Oxford) menciptakan ruang bagi intelektual seperti Galileo dan Newton. Sementara itu, di dunia Islam, madrasah hanya menghasilkan ulama yang fokus pada hukum Islam (fiqh), bukan sains atau filsafat.
Kolonialisme dan Kegagalan Reformasi (Abad ke-19)
Ketika Eropa menjajah dunia Islam pada abad ke-19, ketertinggalan semakin jelas. Upaya reformasi seperti Tanzimat di Ottoman dan modernisasi di Mesir berusaha meniru sistem Barat. Namun, reformasi ini bersifat top-down dan tidak mengubah struktur aliansi ulama-negara. Ulama tetap mempertahankan pengaruh dengan menggalang massa melawan “pengaruh asing”. Misalnya, di Arab Saudi, aliansi antara keluarga Saud dan ulama Wahabi menjadi dasar negara modern.
Kuru menegaskan, reformasi semacam ini gagal karena tidak membuka ruang bagi kelas intelektual dan pedagang independen. Hasilnya, ekonomi tetap bergantung pada sektor tradisional, dan otoritarianisme terus bertahan.
| Periode | Peristiwa/Kebijakan Kunci | Dampak |
| Abad ke-8–11 | – Kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi didukung oleh kemandirian ulama dan pedagang. – Kota seperti Baghdad dan Cordoba menjadi pusat inovasi. – Tokoh seperti Al-Khawarizmi dan Ibnu Sina berkarya tanpa intervensi negara. | – Pertukaran ide lintas peradaban (Yunani, India, Persia). – Ekonomi berbasis perdagangan yang dinamis. – Produktivitas intelektual tinggi. |
| Abad ke-11 | – Aliansi ulama-negara dimulai. – Sistem iqta (pengelolaan tanah untuk militer) diperkenalkan. – Madrasah Nizamiyyah didirikan untuk melatih ulama loyal. – Pemikiran Al-Ghazali diadopsi selektif oleh negara. | – Ulama independen terkooptasi oleh negara. – Pemikiran rasionalis (Mutazilah) ditekan. – Peran pedagang melemah, kontrol ekonomi beralih ke negara. |
| Abad ke-12–14 | – Invasi Mongol (1258) dan Crusader (1096–1291). – Negara bergantung pada legitimasi ulama untuk mobilisasi perlawanan. – Karya filsafat/sains dianggap bidah (contoh: buku Ibnu Rusyd dibakar). | – Aliansi ulama-negara semakin kokoh. – Intelektual independen terpinggirkan. – Madrasah hanya fokus pada kurikulum ortodoks. |
| Abad ke-15–18 | – Bangkitnya kekaisaran Sunni (Ottoman, Safavid, Mughal). – Ulama diintegrasikan ke birokrasi negara. – Perdagangan dikontrol ketat oleh negara. | – Stagnasi ilmu pengetahuan: Tidak ada penemuan besar. – Eropa mengalami Renaisans, sementara dunia Islam tertinggal. – Madrasah hanya menghasilkan ahli fiqh, bukan ilmuwan. |
| Abad ke-19 | – Kolonialisme Eropa dan upaya reformasi top-down (contoh: Tanzimat di Ottoman). – Ulama memobilisasi massa melawan pengaruh asing. | – Reformasi gagal mengubah struktur aliansi ulama-negara. – Ekonomi tetap tradisional, otoritarianisme bertahan. – Muncul reaksi anti-Barat yang konservatif. |
| Kesimpulan | – Aliansi ulama-negara (sejak abad ke-11) menjadi akar kemunduran. | |
Penutup
Kemunduran Islam tidak hanya bisa dijelaskan semata-mata takdir agama, melainkan faktor struktural dari aliansi ulama-negara yang terbentuk sejak abad ke-11. Aliansi ini meminggirkan aktor kunci pembangunan (intelektual dan pedagang) dan menggantikan inovasi dengan kepatuhan pada otoritas.
Penting untuk dipahami bahwa tokoh seperti Al-Ghazali tidak secara langsung menyebabkan kemunduran; dialektika pemikirannya direkayasa oleh kepentingan politik untuk mempertahankan hegemoni. Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan hanya mungkin ketika negara dan agama tidak saling mengontrol, sebagaimana terjadi di masa keemasan Islam.
Terlepas dari berbagai kritik yang mengatakan analisis Kuru terlalu simplifikasi, buku “Islam, Authoritarianism, and Underdevelopment” bukan sekadar buku sejarah, melainkan peta jalan untuk memahami akar krisis dan peluang kebangkitan kembali dunia Muslim. Dengan menggabungkan analisis dan relevansi kontemporer, Kuru memberikan lensa baru yang penting bagi siapa pun yang peduli pada masa depan demokrasi dan pembangunan di negara-negara Muslim.
Penulis: Redaksi Insight by Research





