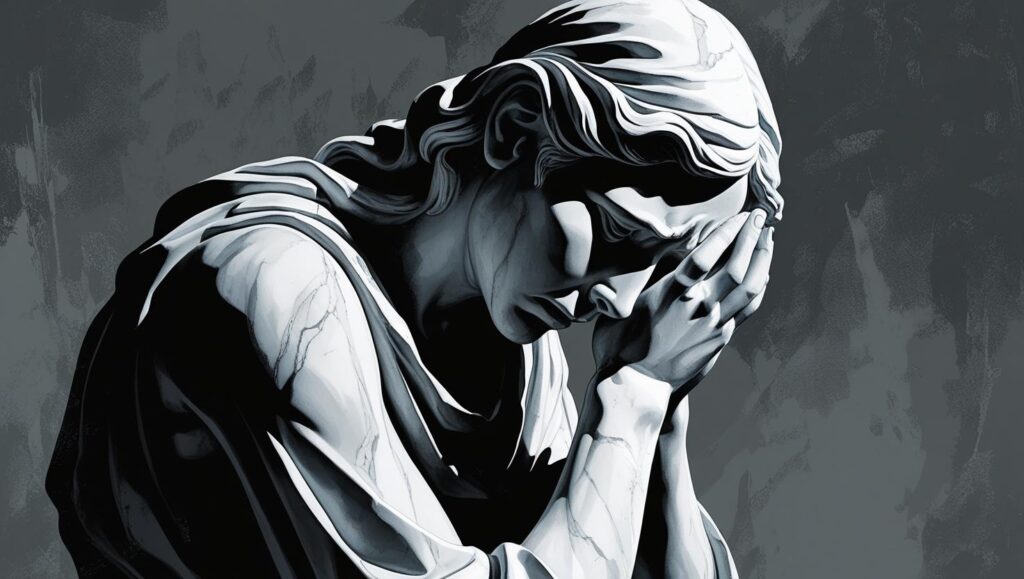Sepanjang sejarah manusia, konsep-konsep religius (seperti dewa yang mengendalikan alam, hantu yang menakutkan, atau mukjizat yang melampaui logika) telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya di berbagai belahan dunia. Fenomena ini memicu pertanyaan mendasar: Mengapa ide-ide yang secara intuitif “tidak masuk akal” justru mudah diingat, diterima, diimani dan menyebar lintas generasi?
Salah satu penjelasan dalam ilmu kognitif agama (cognitive science of religion) adalah Minimally Counterintuitive (MCI), yang dikemukakan oleh Pascal Boyer dan Justin Barrett. Tulisan ini akan menjelaskan secara ringkas tentang minimally counterintuitive dalam menerangkan daya tarik religius, sekaligus memaparkan sebagian hasil uji empiris terhadap klaim-klaimnya.
Minimally Counterintuitive (MCI): Mekanisme Kognitif di Balik Kepercayaan Religius
Minimally Counterintuitive (MCI) adalah teori yang menjelaskan mengapa ide-ide religius, seperti dewa, hantu, atau mukjizat, mudah diingat dan tersebar luas dalam budaya manusia. Minimally counterintuitive merujuk pada konsep yang melanggar satu atau dua ekspektasi intuitif dari kategori ontologis dasar manusia (seperti objek, makhluk hidup, atau agen), tetapi tetap mempertahankan sebagian besar sifat yang sesuai dengan kategori tersebut.
Sebagai penjelasan, kategori ontologis objek fisik (misalnya batu dan meja) seharusnya tidak bergerak sendiri, makhluk hidup (misalnya pohon dan hewan) layaknya bertumbuh dan bereproduksi, agen berpikir (misalnya manusia) memiliki niat dan emosi.
Ketika ada kepercayaan bahwa pohon yang bisa bicara atau berjalan sendiri, sebenarnya melanggar cara kerja ontologis karena pohon (makhluk hidup non-agen) tidak punya kemampuan komunikasi verbal dan tujuan. Namun, pohon dipersepsikan tetap memiliki akar, daun, dan sifat tumbuhan lainnya (fisik).
Contoh lagi yang sering digunakan adalah patung yang menangis. Kepercayaan ini juga melanggar ekspektasi bahwa patung (objek mati) tidak memiliki emosi atau cairan biologis. Tapi, patung tetap berbentuk fisik seperti umumnya patung yang lain. Kedua contoh ini menunjukkan sedikit pelanggaran intuitif dengan tetap mempertahkan kategori ontologis lainnya sehingga menciptakan “keanehan terukur” yang menarik perhatian otak, tanpa membuat konsep tersebut terlalu rumit untuk diproses dan diterima.
Dalam konteks kepercayaan religius, MCI kemudian menjelaskan mengapa ide-ide supernatural mudah diterima dan bertahan. Studi Gibbon (2008) berjudul “God is great, God is good: Teaching god concepts in Turkish Islamic sermons” memberikan contoh tentang hal ini dengan contoh kasus khotbah Islam di Turki. Dalam khotbah, Allah sering digambarkan dengan atribut seperti “Maha Mengetahui” (tahu segala hal tanpa proses belajar) atau “Maha Hadir” (berada di semua tempat sekaligus).
Kedua sifat ini melanggar keterbatasan manusia, kita harus belajar untuk mengetahui sesuatu dan hanya bisa berada di satu lokasi dalam satu waktu, tetapi tetap mempertahankan konsistensi ontologi dengan kategori “agen super” yang menguasai alam semesta (dengan memiliki kehendak). Pelanggaran minimal secara intuitif ini membuat konsep Allah mudah diingat sekaligus dipahami sebagai entitas yang transenden.
Mekanisme MCI juga terlihat dalam konsep-konsep seperti hantu atau roh leluhur. Misalnya, hantu yang bisa menembus tembok menggabungkan sifat manusia (memiliki emosi dan niat) dengan kemampuan melanggar hukum fisika. Meski aneh, konsep ini tidak sepenuhnya asing karena mempertahankan sifat agen seperti kemarahan atau keinginan untuk berkomunikasi.
Titik tekan penjelasan MCI terletak pada keseimbangannya antara keunikan dan kemudahan pemrosesan dalam pikiran manusia. Konsep yang terlalu intuitif biasa (misalnya, “batu biasa”) akan cenderung membosankan dan mudah dilupakan. Sebaliknya, konsep yang terlalu absurd (misalnya, “batu yang bisa bicara 7 bahasa, terbang, dan menghilang”) sulit dipahami karena melanggar terlalu banyak ekspektasi sekaligus.
MCI berada di “titik tengah” antara keduanya, seperti bumbu dalam masakan yang cukup unik untuk menarik selera, tapi tidak sampai mengubah rasa sepenuhnya. Analogi ini membantu menjelaskan mengapa agama-agama dunia seringkali memiliki konsep serupa, seperti dewa penguasa alam (Zeus dengan petir) atau roh penjaga (arwah leluhur) yang semuanya memenuhi kriteria MCI.
Kerangka ini menunjukkan bahwa MCI tidak sekadar hanya teori abstrak, melainkan mekanisme kognitif yang menjelaskan keumuman agama. Konsep-konsep religius bertahan karena memanfaatkan cara kerja otak manusia: kita tertarik pada hal yang sedikit mengejutkan, tetapi hanya mampu memproses informasi yang tidak terlalu kompleks. Seperti puzzle dengan satu keping yang hilang, MCI menciptakan daya tarik tanpa mengorbankan koherensi, sebuah resep kuno yang membuat agama tetap relevan hingga hari ini.
Pengujian Minimally Counterintuitive (MCI)
Sejumlah penelitian telah melakukan pengujian terhadap Minimally Counterintuitive (MCI). Misalkan penelitian Sommer (2023) dalam risetnya berjudul “Counterintuitive Concepts Across Domains: A Unified Phenomenon“. Sommer melakukan eksperiman terkontrol untuk membandingkan konsep MCI seperti “pohon yang menjadi muda setiap dua tahun” (melanggar ekspektasi biologis) dibandingkan dengan konsep bizarre (BIZ) seperti “lampu senilai $30.000”.
Hasilnya, ketika faktor seperti inferential potential (kemampuan memicu pemikiran) dan tingkat keanehan dikontrol, tidak ada perbedaan signifikan dalam daya ingat antara kedua kategori. Keduanya lebih mudah diingat daripada konsep intuitif standar, misalnya kursi kayu. Artinya, MCI bukan sebuah mekanisme kognitif yang memiliki keunggulan khusus dalam menjelaskan cara kerja otak menerima konsep spritual, namun sama halnya dengan efek psikologis umum seperti von Restorff effect, yakni kecenderungan otak mengingat hal yang mencolok, daripada keunikan pelanggaran ontologis.
Dengan kata lain, temuan tersebut mengindikasikan bahwa MCI mungkin bukan mekanisme kognitif yang unik, melainkan bagian dari fenomena lebih luas tentang bagaimana otak memproses informasi yang tidak biasa.
Penelitian lain mencoba menguji MCI secara spesifik dalam konteks religius. Misalkan penelitian yang telah disinggung di bagian sebelumnya, yakni analisis teks keagamaan oleh Gibbon (2008) pada 295 teks khotbah Islam di Turki.
Dalam khotbah, Allah kerap digambarkan dengan atribut MCI seperti “Maha Mengetahui” atau “Maha Hadir” (berada di semua tempat). Meski melanggar ekspektasi manusia tentang keterbatasan pengetahuan dan ruang, sifat-sifat ini tetap mempertahankan konsistensi sebagai agen super yang menguasai alam semesta.
Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa konsep Allah tidak pernah mengandung lebih dari dua pelanggaran ontologis dalam satu deskripsi. Misalnya, Allah tidak digambarkan sekaligus dalam satu waktu sebagai “makhluk abadi yang tidak perlu makan, menembus tembok, dan membaca pikiran”, kombinasi ini akan dianggap terlalu rumit (maximally counterintuitive). Hal ini menunjukkan bahwa praktik doktrin agama secara alami membatasi kompleksitas konsep supernatural untuk menjaga keseimbangan antara keunikan dan koherensi.
Lebih lanjut, penelitian Beebe dan Duffy (2020) berjudul “The Memorability of Supernatural Concepts: Effects of Minimal Counterintuitiveness, Moral Valence, and Existential Anxiety on Recall” mengungkap bahwa faktor di luar MCI, seperti muatan moral dan kecemasan eksistensial manusia, berperan besar dalam memperkuat daya ingat konsep religius.
Dalam studi eksperimen, konsep seperti “patung yang menangis saat penduduk berbuat dosa” (menggabungkan MCI dengan muatan moral negatif) diingat lebih baik daripada konsep MCI tanpa konteks moral, seperti “batu yang bisa bicara” saja.
Demikian pula, konsep yang terkait kecemasan eksistensial (misalnya, “roh yang mengawasi orang sekarat”) memiliki daya ingat tinggi meski tidak melanggar ekspektasi ontologis. Temuan ini menegaskan bahwa MCI hanyalah salah satu komponen dalam jaringan narasi religius.
Kekuatan konsep religius tidak hanya terletak pada keanehannya dalam memicu data tarik otak, tetapi juga pada kemampuannya menjawab pertanyaan mendasar manusia, seperti makna hidup, moralitas, atau ketakutan akan kematian, yang membuatnya relevan secara emosional dan kultural.
Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun MCI layaknya konsep umum psikologi bahwa manusia terpicu untuk tertarik pada hal yang unik, namun konsep ini bisa menjelaskan mekanisme kognitif dibalik kepercayaan pada aspek religius, tetapi daya tahannya bergantung pada integrasi dengan elemen lain seperti narasi moral, ritual, dan kebutuhan psikologis.
Lain kata, agama tidak sekadar kumpulan ide aneh, melainkan sistem konseptual yang “terukur” dalam keanehannya, cukup unik untuk menarik perhatian, sekaligus cukup koheren untuk dijadikan dasar keyakinan dan praktik sehari-hari.
Penutup
Minimally Counterintuitive (MCI) memberikan perspektif kognitif yang menarik untuk memahami mengapa konsep religius, dari dewa-dewa kuno hingga roh penjaga, mampu bertahan dalam ingatan kolektif manusia. Namun, temuan empiris juga mengungkap bahwa MCI hanyalah salah satu bahan dalam “resep kognitif” agama. Faktor seperti muatan moral, kecemasan eksistensial, dan kemampuan membangun narasi (inferential potential) turut memperkuat daya tahan konsep religius.
Agama tidak hanya menawarkan keanehan, tetapi juga jawaban atas pertanyaan mendasar manusia: Mengapa kita ada? Apa yang terjadi setelah mati? Bagaimana harus hidup? Konsep MCI, seperti Allah yang “Maha Mengetahui” atau patung yang menangis, menjadi alat untuk merangkai jawaban-jawaban ini dalam bentuk yang mudah diceritakan dan diwariskan.
Pada akhirnya, MCI bukanlah penjelasan tunggal, melainkan bagian dari mekanisme evolusi budaya yang lebih luas. Lain kata, konsep religius bertahan karena mereka memanfaatkan kelemahan dan kekuatan otak manusia, dalam bentuk ketertarikan pada hal yang tidak biasa, sekaligus kebutuhan akan makna serta hasrat untuk terhubung dengan sesuatu yang transenden.
Penulis: Redaksi Insight by Research