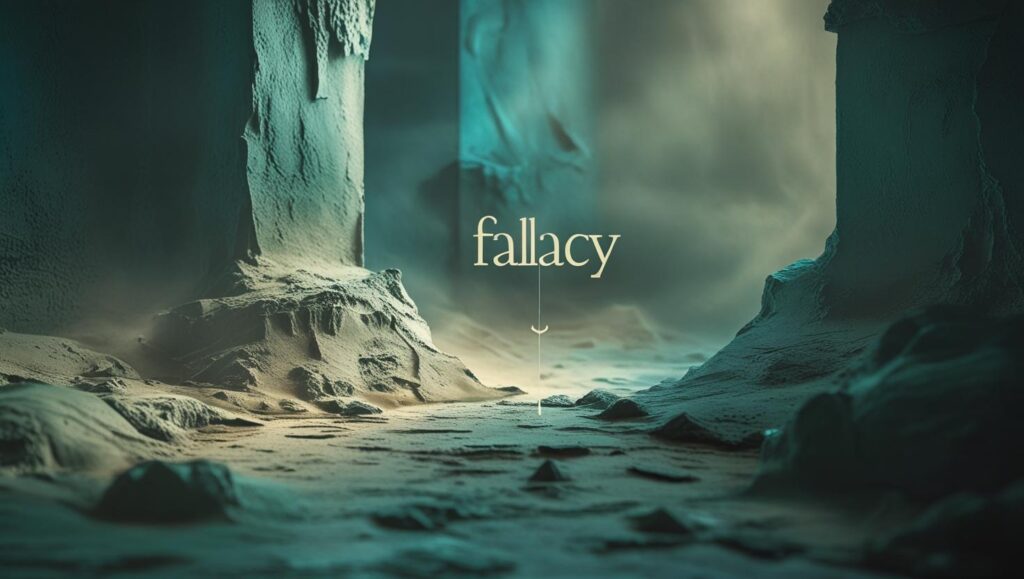Sebagai makhluk rasional, manusia memiliki kemampuan untuk berpikir, menganalisis, dan menarik kesimpulan. Namun, proses penalaran tidak selalu berjalan sempurna. Terkadang, kita terjebak dalam kesalahan logika yang disebut sesat pikir atau logical fallacy. Dengan demikian, singkatnya, sesat pikir adalah adanya kesalahan dalam penalaran akibat mengabaikan aturan logika tertentu.
Agar lebih mudah dipahami, tulisan singkat ini akan memaparkan sejumlah konsep penting yang terkait dengan sesat pikir, yakni pengertian penalaran, argumen, keyakinan, dan pengertian sesat pikir. Keterangan yang diuraikan bersumber dari buku “Logically Fallacious: The Ultimate Collection of Over 300 Logical Fallacies (Academic Edition)” (2020) yang ditulis oleh Bo Bennett.
Pengertian Penalaran (Reasoning)
Penalaran, sederhananya, adalah proses mental untuk menetapkan atau memprediksi fakta, mengubah keyakinan, atau membuat kesimpulan berdasarkan bukti dan logika. Kemampuan ini memungkinkan manusia untuk memahami dunia sekitar, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan.
Misalnya, ketika seseorang melihat langit mendung dan mendengar berita siaran cuaca tentang hujan, dia mungkin mengambil kesimpulan hujan akan turun (memprediksi) sehingga dia membawa payung sebelum keluar rumah (mengambil kesimpulan yang menuntun keputusan). Proses penalaran melibatkan pengolahan informasi dari pengalaman atau pengetahuan sebelumnya.
Dalam konteks akademis, penalaran dibagi menjadi dua jenis: deduktif dan induktif. Penalaran deduktif dimulai dari pernyataan umum menuju kesimpulan spesifik. Contoh klasik adalah:
Premis 1: Semua manusia akan mati.
Premis 2: Socrates adalah manusia.
Kesimpulan: Maka, Socrates akan mati.
Jika premis benar, kesimpulan deduktif pasti valid. Sementara itu, penalaran induktif bersifat probabilistik, seperti kesimpulan bahwa “matahari akan terbit besok” karena telah terbit setiap hari selama ribuan tahun. Meski kuat, kesimpulan ini tidak mutlak, bisa saja suatu hari matahari tidak terbit akibat fenomena kosmik.
Di Indonesia, contoh penalaran induktif dapat dilihat dalam kepercayaan tradisional, seperti “jika burung gagak berkokok di malam hari, pertanda akan ada musibah.” Meski tidak ilmiah, keyakinan ini terbentuk dari pengamatan berulang yang dianggap memiliki pola sebagai dasar penalaran.
Pengertian Argumen
Setelah memahami bagaimana penalaran bekerja, penting untuk melihat bagaimana proses tersebut diwujudkan dalam bentuk argumen. Dalam logika, argumen bukanlah perdebatan emosional, melainkan serangkaian pernyataan yang disusun untuk mendukung suatu kesimpulan.
Argumen terdiri dari premis (alasan) dan kesimpulan. Sebagai contoh, mari kita ambil fenomena viral di media sosial:
Premis 1: Video TikTok seorang influencer menunjukkan bahwa minum air rebusan daun sirih dapat menyembuhkan diabetes.
Premis 2: Video tersebut telah ditonton oleh 5 juta orang dan mendapat ribuan komentar positif.
Kesimpulan: Jadi, air rebusan daun sirih efektif menyembuhkan diabetes.
Tanpa premis yang valid, klaim tersebut hanyalah opini yang tidak terbukti. Argumen menjadi landasan untuk membedakan antara informasi yang berdasar dan sekadar klaim subjektif. Sayangnya, banyak argumen sehari-hari mengandung kelemahan.
Contoh lain adalah pernyataan: “Aplikasi investasi X banyak diikuti anak muda, jadi pasti aman dan menguntungkan.” Padahal, popularitas tidak menjamin keamanan, bisa saja aplikasi tersebut adalah skema Ponzi yang belum terbongkar.
Argumen yang baik membutuhkan premis yang relevan dan kuat. Misalnya, dalam kasus kebijakan pemerintah tentang subsidi BBM:
Premis 1: Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa 60% subsidi BBM dinikmati oleh kalangan menengah ke atas.
Premis 2: Pengalihan subsidi ke program sosial dapat mengurangi ketimpangan ekonomi.
Kesimpulan: Oleh karena itu, pemerintah perlu merevisi kebijakan subsidi BBM.
Di sini, premis berbasis data dan logika yang jelas, sehingga kesimpulan lebih dapat dipertanggungjawabkan.
Kepercayaan (Beliefs)
Setelah mengeksplorasi bagaimana argumen dibangun, kita perlu memahami peran keyakinan dalam membentuk pemikiran. Keyakinan adalah proposisi yang dianggap benar oleh seseorang, terlepas dari apakah didukung bukti atau tidak.
Keyakinan bisa berasal dari budaya, agama, pengalaman pribadi, atau doktrin. Misalnya, sebagian masyarakat Bali percaya bahwa ngaben (upacara kremasi) diperlukan agar arwah mencapai alam spiritual. Keyakinan ini mungkin didasarkan pada warisan leluhur, bukan analisis ilmiah.
Namun, tidak semua keyakinan irasional. Ada juga keyakinan yang dibangun melalui penalaran, seperti kepercayaan bahwa “penggunaan helm mengurangi risiko cedera kepala saat berkendara.”
Keyakinan ini didukung data kecelakaan dan penelitian keselamatan transportasi. Persoalan muncul ketika keyakinan tidak diuji secara kritis, terutama jika berdampak luas.
Contoh ekstrem adalah kepercayaan bahwa orang gondrong (yang merupakan bagian dari stigma hasil Orde Baru) pasti berperilaku buruk. Meski tidak ada bukti empiris, stereotip ini masih hidup di sebagian masyarakat Indonesia dan memicu pandangan negatif.
Penting untuk membedakan antara keyakinan yang sehat (berdasarkan bukti) dan keyakinan dogmatis (tanpa dasar logis). Evaluasi kritis terhadap keyakinan pribadi maupun kolektif diperlukan untuk menghindari penyebaran misinformasi.
Arti Sesat Pikir (Logical Fallacy)
Dari pemaparan tentang penalaran, argumen, dan keyakinan, muncul pertanyaan: lantas, apa tepatnya sesat pikir itu?
Secara etimologis, istilah logical fallacy, yang dalam Bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai sesat pikit, berasal dari kata Latin fallacia, yang berarti “penipuan” atau “tipu daya”. Dalam konteks logika, istilah ini pertama kali digunakan pada abad ke-16 untuk menggambarkan argumen yang keliru atau tidak sahih.
Menurut William Stanley Jevons dalam buku “Elementary Lessons in Logic: Deductive and Inductive” (1870), sesat pikir didefinisikan sebagai “kesalahan dalam penalaran akibat mengabaikan aturan logika”.
Lain kata, sesat pikir bukanlah kesalahan fakta (seperti menyebut “Jakarta adalah ibu kota Malaysia”), melainkan kesalahan dalam cara kita menghubungkan premis-premis untuk mencapai kesimpulan.
Sebagai contoh, perhatikan pernyataan ini: “Presiden Jokowi sering mengenakan kemeja putih, dan selama masa jabatannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil. Jadi, kemeja putih adalah faktor penstabil ekonomi.”
Ini adalah post hoc ergo propter hoc, yakni mengasumsikan bahwa karena dua peristiwa terjadi berurutan, maka satu pasti penyebab yang lain. Padahal, korelasi tidak selalu berarti sebab-akibat.
Contoh lain dalam bentuk appeal to tradition: “Kita harus terus melakukan larung sesaji ke laut karena nenek moyang kita selalu melakukannya.” Argumen ini menganggap tradisi sebagai pembenaran mutlak, tanpa mempertimbangkan relevansi atau bukti aktual.
Untuk memperjelas pengertian dasar dari sesat pikir, Bo Bennett menjelaskan perbedaan antara antara sesat pikir dan cognitive biases (bias kognitif) yang terletak pada konteksnya. Sesat pikir memerlukan argumen yang mengandung kesalahan logika, sementara cognitive biases adalah pola pikir tidak sadar yang memengaruhi keputusan.
Misalnya, bandwagon effect (kecenderungan mengikuti tren) adalah bias kognitif, tetapi ketika diwujudkan dalam argumen seperti “Produk ini telah terjual hingga 2 juta kali, jadi ini pasti bagus,” hal itu menjadi appeal to popularity fallacy (salah satu bentuk cacat logika). Pendapat atau kepercayaan yang telah diterima banyak orang tidak selalu menjadi tolok ukur kebenaran ilmiah.
Hal ini menegaskan bahwa sesat pikir tidak terkait dengan kesalahan fakta data, seperti mengira matahari berjarak 30 mil dari Bumi, namun kesalahan dalam melakukan penalaran sehingga tidak memenuhi aturan logika hingga sampai pada kesimpulan.
Penulis: Redaksi Insight by Research
Baca Juga:
Apa Benar IQ Orang Indonesia itu 78,5?
Cognitive Science of Religion (CSR): Menelusuri Sejarah dan Perkembangannya dalam Memahami AgamaMinimally Counterintuitive (MCI), Mekanisme Kognitif Mengapa Konsep Religius Mudah Diterima dan Diingat?